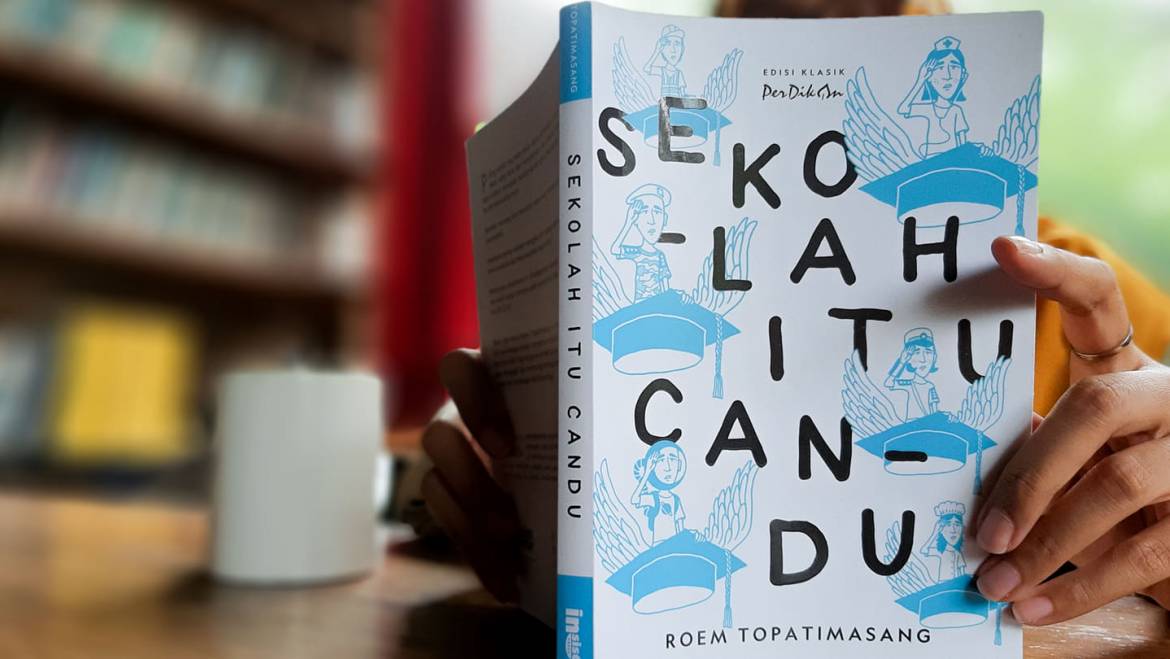Penulis: Roem Topatimasang, Sekolah Itu Candu (Edisi Klasik Perdikan), INSISTPress 2020
Zoonosis?
Binatang apa pula ini?
BUKAN, ini bukan binatang, tapi penyakit (atau lebih tepatnya: virus penyebab penyakit) pada binatang yang menular ke manusia. Karena dulu pernah belajar bahasa Latin, saya tahu arti harfiahnya. Dari akar kata zoon (binatang, hewan), dan nosos (sakit, penyakit[an], ke[ter]sakitan).
Lalu, apa pengertian dan maksud sebenarnya?
Sampai sekarang pun, saya masih sering bertemu dengan banyak orang, termasuk kalangan terpelajar dan sarat informasi, yang mengaku baru mendengar dan tahu tentang istilah itu. Saya sendiri juga mendapat penjelasannya baru beberapa tahun lalu—maaf, agak lupa, kalau tak salah: 2011. Waktu itu, saya diminta memandu (memfasilitasi) satu pertemuan nasional para dokter hewan se-Indonesia, di Bogor. Para dokter hewan yang berkumpul di sana membahas beberapa topik yang, menurut mereka, sudah sangat penting dan mendesak untuk diperhatikan secara khusus dan bersungguh-sungguh. Salah satunya adalah soal kemungkinan semakin maraknya ancaman penyebaran penyakit hewan sampai ke tingkat wabah yang juga menyerang manusia. Ya, zoonosis!
Saya bukan dokter hewan. Jadi, saya mengikuti perbincangan mereka tidak lagi sekadar sebagai fasilitator saja, tapi juga sekaligus sebagai ‘murid’ yang belajar tentang sesuatu yang saya masih sangat awam. Dari perbincangan mereka itulah saya mulai dan kian paham bahwa ancaman bahaya penularan penyakit hewan ke manusia di negeri ini, bahkan juga di seluruh dunia, benar-benar nyata dan tak boleh lagi dipandang enteng. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah ketika mereka mengemukakan fakta kian sulitnya memperoleh data yang terus terbarukan (updated) secara langsung dan cepat dari lapangan tentang berbagai hal menyangkut kesehatan dan kesejahteraan hewan: jumlah dan jenisnya, persebaran dan pergerakannnya secara spasial, jenis dan cara penangggulangan penyakitnya, dan sebagainya. Padahal, kata mereka, data-dasar (baseline) itulah yang sangat menentukan pada tingkat pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala dan kejadian zoonosis pada suatu wilayah tertentu, sumber asal muasal utamanya, jenis virus dan modus (cara dan mata rantai) serta kecepatan persebarannya, sehingga akan lebih memudahkan untuk merancang kemungkinan pencegahannya, dan seterusnya.
Ada banyak sebab yang membuat masalah ruwet itu. Yang paling menonjol dan memang jadi biang kerok adalah ketaksiapan perangkat pendataan dan pemantauan di aras terbawah di lapangan. Jumlah pos pemeriksaan atau karantina hewan masih sangat kurang dan tidak tersebar merata, sementara jumlah tenaga profesional kesehatan hewan (dokter, mantri, petugas teknis pendukung) pun masih keteteran.1
Terkait dengan pokok permasalahannya, tentang kesulitan mendapatkan data langsung dan cepat dari lapangan, mereka mengakui bahwa yang memegang peran kunci adalah para mantri hewan yang bekerja di akar rumput. Para dokter hewan yang berkumpul di Bogor waktu itu mempersoalkan keputusan pemerintah yang mengurangi, bahkan menghapuskan sama sekali, program pendidikan kedinasan yang selama ini melahirkan tenaga-tenaga mantri hewan. Menurut mereka, keputusan itu tidak memiliki dukungan data dan alasan yang kuat.2
Saya sangat sependapat dengan para dokter hewan itu. Pengalaman masa kecil saya menyaksikan bagaimana para petani di pedesaan terpencil sekalipun sangat tertolong oleh kehadiran para mantri di berbagai bidang yang mereka butuhkan. Mereka yang seusia dengan saya, yang lahir dan tumbuh di kawasan pedesaan pada dasawarsa 1950 dan 1960-an, tak akan asing dengan istilah-istilah ‘Mantri Hewan’, ‘Mantri Cacar’, ‘Mantri Air’, ‘Mantri Hutan’, dan sebagainya. Para mantri itu adalah orang-orang yang sangat dihormati oleh warga pedesaan, karena mereka hampir selalu siap dan hadir saat dibutuhkan.
Meskipun juga melakukan tugas-tugas seperti yang dilakukan para penyuluh lapangan (extension workers) yang kita kenal sekarang, namun mereka berbeda dalam banyak hal. Antara lain, mereka selalu dengan ringan tangan dan sukarela siap membantu melakukan pekerjaan yang bukan tugas utamanya, misalnya, mengajar di sekolah-sekolah kampung, ikut gotong royong atau kerja bakti, mengantar warga mengurus berbagai hal di kota kecamatan atau kabupaten, dan masih banyak lagi. Saya masih ingat tak pernah melihat para mantri itu berpakaian seragam dinas, atau berceramah di depan kumpulan besar warga, apalagi membawa-bawa dan menyebarkan poster-poster reklame berbagai produk pertanian (benih, pupuk, racun hama, dan sebagainya) seperti banyak penyuluh pertanian lapangan (ppl) masa kini. Pakaian mereka sehari-hari sama seperti warga lainnya. Kalau menjelaskan sesuatu, tidak pernah di ruangan, tapi langsung di tempat mereka melakukan tugas lapangan (sawah, ladang, kolam ikan, kandang ternak, pondok hutan, dsb.).3
Ya, para pekerja lapangan berkemampuan, berkepribadian, dan penuh pengabdian macam para mantri tempo doeloe itulah yang kian kita butuhkan kini, zaman di mana wabah zoonosis semakin banyak dan kian sering muncul. Dalam senarai panjang dari organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) terdaftar paling tidak ada 67 jenis virus zoonosis yang pernah mewabah dan mematikan jutaan manusia, terhitung setelah petaka sampar mengerikan ‘Maut Jelaga’ (Black Death) abad ke-14 di Eropa.4 Selama abad ke-21 saja— yang baru berlangsung seperlima kurun saat ini—sudah tercatat tiga wabah zonoosis yang bikin dunia panik dan limbung: penyakit parah saluran pernapasan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (2003), ‘flu babi’ H1N1 (2009), dan korona baru atau Covid-19 sekarang ini (2019–2020). Di sela-sela tiga wabah mendunia (pandemi) itu, ada beberapa wabah zoonosis lainnya muncul secara kawasan (epidemi): ‘demam Sungai Nil Barat’ (West Nile fever) (2002), ‘flu burung’ H5N1 (2003), ‘penyakit saluran pernafasan Timur Tengah’ (Middle East Respiratory Syndrome [MERS]) (2012), ebola (2014), zika (2015), dan ‘demam Ngarai Rift’ (Rift Valley fever) (2016).5
Sekolah-sekolah khusus kedinasan dan kejuruan—juga program-program diploma tanpa gelar (non-degree) di perguruan tinggi—sebenarnya dirancang untuk menghasilkan tenaga-tenaga teknis profesional tingkat menengah yang handal. Ya, para ‘mantri’! Tetapi, sampai sekarang, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tetap tertinggal jauh dibanding jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) (SMK = 8.458; SMA+MA = 19.173).6 Sementara itu, persebaran jumlah siswa SMK pada semua jurusan juga memperlihatkan bahwa jurusan-jurusan pertanian dan pedesaan serta yang berkaitan—termasuk jurusan kesehatan hewan—masih tetap saja di bawah jurusan-jurusan bukan pertanian dan pedesaan atau yang berkaitan dengannya. Sampai akhir 2018, jumlah siswa seluruh jurusan ‘ndeso’ (yang tergabung dalam rumpun keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi yang terdiri atas enam jurusan, termasuk jurusan Kesehatan Hewan) di SMK tercatat 229.236 orang, berada pada peringkat kelima, di bawah semua jurusan ‘ngota’: bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa (1.656.710 orang), Bisnis dan Manajemen (1.250.157), Teknologi Informasi dan Komunikasi (1.133.314), dan Pariwisata (378.679).7 Sementara itu, di tingkat pendidikan tinggi, jumlah mahasiswa di semua jalur program diploma (D1 sampai D4) di seluruh perguruan tinggi di Indonesia pun kurang dari seperenam (15,2%) dari jumlah mahasiswa di jalur S1 (84,8%).8
Ya, saat kita kian membutuhkan lebih banyak ‘mantri’, sekolah-sekolah khusus untuk menghasilkannya justru masih tetap bukan yang paling dikedepankan dalam kebijakan dan strategi pengembangan sistem pendidikan kita. Akhir 2018, Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah dan Kejuruan secara resmi menambah empat jurusan baru SMK: Ritel, Manajemen Logistik, Hotel dan Restoran, dan Produksi Film!9
Nah, tak satu pun yang merupakan jurusan dalam bidang keahlian pertanian dan pedesaan atau yang berkaitan langsung dengannya. Pendulum memang sedang bergerak ke arah yang berlawanan!
Setahun kemudian, jelang akhir 2019, virus korona baru mulai merebak di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Hanya dalam hitungan minggu, virus itu menjadi wabah mendunia. Awal Februari 2020, Menteri Kesehatan Republik Indonesia—dalam kabinet baru yang jumlah menterinya tambah banyak dan baru dilantik beberapa minggu sebelumnya—muncul di beberapa saluran televisi nasional dengan nada bangga menyatakan bahwa negeri ini sudah siap mencegah serbuan virus itu. Dia menyatakan sudah melakukan koordinasi ke daerah-daerah, mememeriksa kesiapan semua sarana, termasuk laboratorium, yang diperlukan untuk pemeriksaan virus dan pencegahan wabah. Dia membantah keras tudingan seorang pakar penyakit mewabah (epidemologi) di Amerika Serikat bahwa virus itu sebenarnya sudah masuk ke Indonesia, dan bahwa sarana laboratorium penjejak virus di negeri ini belum memadai dari segi jumlah maupun kemampuan.
Belum sebulan, ‘Sang Korona’ mempermalukan Sang Menteri. Ratusan kasus positif Covid-19 muncul di banyak tempat, terutama di wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Rentetan kejadian itu mengingatkan saya pada peringatan para dokter hewan yang bertemu di Bogor pada 2011: akibat lemahnya perangkat kerja, termasuk kurangnya tenaga teknis madya yang bekerja langsung di lapangan, sulit mendapatkan data yang terus terbarukan secara langsung dan cepat. Akibatnya, seorang menteri dengan mudah terkelabui dan membuat pernyataan gegabah. Maka, saya pun sulit untuk tidak mengiyakan peringatan para dokter hewan yang dulu saya fasilitasi bertemu di Bogor itu: ya, sekarang ini, kita butuh lebih banyak ‘mantri’, bukan ‘menteri’!
SEMPU, 20 Mei 2020
Catatan
1 Waktu itu (2011), mereka menyebut jumlah dokter hewan se-Indonesia berada pada kisaran 10 ribuan orang, sementara yang dibutuhkan sekitar 20 ribuan. Delapan tahun kemudian (2019), Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), menyebut rekan sejawatnya di seluruh negeri sudah mencapai 20 ribuan orang, tapi jumlah yang dibutuhkan juga sudah meningkat menjadi 70 ribuan orang, sehingga masih tetap tekor sekitar 50 ribuan orang (https://www. cnnindonesia.com, 12 Februari 2019).
2 Waktu itu, mereka menyebut beberapa Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Menteri (Permen) yang berisi keputusan tersebut. Saya sudah lupa nomor-nomornya, sementara catatan-catatan saya dari pertemuan itu juga tak bisa saya temukan lagi. Saya cari di internet, juga tidak ketemu. Baru pada 2016 saya mendengar ada kursus singkat di Universitas Brawijaya, Malang, melatih orang menjadi mantri hewan, itu pun terbatas hanya pada penguasaan teknologi inseminasi buatan (IB).
3 Gambaran lebih rinci dan penuh nuansa tentang bagaimana seorang ‘mantri’ masa itu bekerja di pedalaman pedesaan dapat dibaca, antara lain, dalam satu buku yang ditulis oleh seorang dokter relawan di pedesaan Filipina: Juan M. Flavier (1970), Doctor de Barrios (‘Dokter Kampung’), Manila: New Day Publisher. Pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ir. Rochim Wirjowidjojo, Desa Bahagia, Jakarta: CARE Indonesia (1974). Sayangnya, saya belum pernah menemukan buku serupa yang sebagus itu oleh para mantri dan relawan perintis di Indonesia pada masa yang sama.
4 Selengkapnya, lihat: World Health Organization (WHO), “Zoonoses and the Human-Animal-Ecosystems Interface”, Desember 2014. Lihat juga: Dorothy Crawford (2018), Deadly Companions: How Microbes Shaped Our History, Oxford University Press.
5 Tri Satya Putri Naipospos (2020), “Zonoosis Abad Ini,” Kompas 19 Juni.
6 Selanjutnya, lihat https:\\datapokok.ditpsmk.net.
7 https:\\datapokok.ditpsmk.net.
8 Selanjutnya, lihat https:\\www.pddikti.kemdikbud.go.id.
9 Lihat kembali https:\\datapokok.ditpsmk.net.