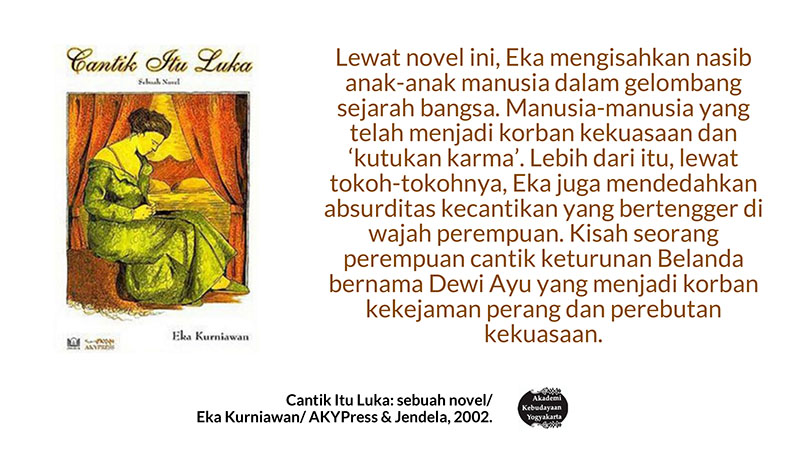Kisah Si Cantik yang Buruk Rupa*
EKA Kurniawan, tampaknya sungguh-sungguh ingin menjadi seorang sastrawan. Setelah menerbitkan kumpulan cerpen dalam antologi Corat-coret di Toilet (1999), alumnus Fakultas Filsafat UGM ini tampaknya tak mau kepalang tanggung dengan merilis sebuah novel. Meski namanya belum begitu “terdengar” dalam belantara sastra, namun novel Cantik Itu Luka ini, begitu diluncurkan ke pasaran, tak berlebihan kalau membuat kalangan sastra sempat tercengang, kagum, dan bahkan hampir tak percaya.
Bagaimana tidak? Novel Cantik Itu Luka dengan tebal 517 halaman bisa dikatakan telah mencatat rekor baru dalam sejarah perjalanan novel Indonesia sebagai novel paling tebal yang dihasilkan sebagai karya perdana. Selain itu, lewat novel ini pengarang juga telah melakukan inovasi baru berkaitan dengan model estetika serta gaya penceritaan sebagai satu bentuk pemberontakan atas mainstream umum. Meski tak dipungkiri masih tampak kuatnya pengaruh dari realisme sosialis yang dikembangkan Pramoedya –sosok yang dikagumi dan sempat diangkat pengarang untuk sebuah skripsinya; Realisme Sosialis Pramoedya Ananta Toer, Suatu Tinjauan Filsafat Seni.
Seperti cerita yang dikembangkan dalam Corat-coret di Toilet, novel ini tak kehilangan gaya khas Eka Kurniawan yang lugas, lancar dan terkadang dengan sense of humor yang tinggi. Bahkan, dengan cukup realis, pembaca dibawa memasuki sejarah bangsa dengan berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi, sebuah potret buram sejarah Indonesia dari masa kolonialisme Jepang hingga pemberontakan PKI.
Lewat novel ini, Eka dengan cukup cerdas dan cerdik mengisahkan nasib anak manusia dalam gelombang sejarah bangsa. Ia telah menjadi korban kekuasaan dan kutukan karma. Lebih dari itu, lewat tokoh-tokohnya, ia juga mencecapkan renungan filosofis yang disematkan pada absurditas kecantikan yang bertengger di wajah perempuan. Tetapi dengan nada ironis, pengarang memaknai kecantikan tak lebih sebagai keindahan sekaligus keburukan (luka). Novel ini mengisahkan seorang perempuan cantik keturunan Belanda bernama Dewi Ayu. Akibat kekejaman kolonialis Jepang, ia ditawan dan dijadikan pelacur.
Tak ayal, kemenangan Jepang atas Belanda telah mengubah nasibnya menjadi amat tragis. Begitu usianya menginjak delapan belas tahun dan kemolekan tubuhnya telah merangsang libido tentara-tentara Jepang, jadilah ia “menu daging segar yang renyah untuk ditiduri”. Di kamp tentara Jepang itu, setidaknya ia telah jadi saksi adanya tindakan biadab tentara Jepang terhadap kaum perempuan. Ia baru bebas ketika Indonesia merdeka.
Meski sudah merdeka, kehidupan buram yang dilakoninya sebagai pelacur ternyata tak juga urung diakhiri. Ia masih melanjutkan kariernya sebagai penjaja tubuh di kota kelahirannya, Halimunda. Bahkan, berkat kecantikannya yang tak tertandingi, ia jadi pelacur idola yang diburu setiap lelaki hidung belang. Selama bertahun-tahun, karier itu dijalaninya hingga ia punya tiga anak gadis. Semua berwajah cantik. Akan tetapi, kecantikan ketiga anak itu tak ubahnya sebuah pisau bermata ganda. Pada satu sisi merupakan anugerah, pada sisi yang lain kehadiran tiga gadis cantik itu sebuah petaka. Sehingga, akibat kutukan dan dosa yang ditanggung Dewi Ayu, ketiga anaknya jadi janda semua. Suami-suami mereka mati mengenaskan.
Untuk itu, tatkala ia mengandung anaknya yang keempat, ia berharap anak itu akan lahir buruk rupa. Tapi, anehnya, ia malah menamai anak keempatnya itu dengan si Cantik. Dia juga bersyukur karena banyak orang mencemooh kondisi anaknya yang wajahnya mirip monster itu. Karena dengan cemoohan itu diharapkan bisa menghilangkan kutukan yang diterimanya selama ini.
Meski buruk muka, si Cantik justru dicintai Krisan, yang tak lain keponakannya sendiri. Bagi Krisan –yang pernah patah hati–, cantik itu ternyata tak lebih sebuah luka. Sehingga tak ada bedanya mencintai si buruk atau si cantik.
Membaca novel ini, kita dibawa ke mana-mana. Hampir semua peristiwa yang dikisahkan ibarat sebuah kaca prisma, yang membiaskan semuanya bisa saling bertabrakan. Itu tak lain karena pengarang kurang cermat dan seolah-olah mau bercerita dengan kemauannya sendiri tanpa mempertimbangkan logika dan fakta sejarah. Tak heran, absurditas yang tak masuk akal seperti dijungkirbalikkan dalam kerangka estetika yang asal comot. Sehingga membuat pembaca bertanya-tanya. Misalnya tentang kebangkitan Dewi Ayu yang telah mati selama dua puluh satu tahun.
Kendati demikian, novel yang coba mengangkat setting sejarah kota Halimunda ini dengan rentetan peristiwa penting bangsa, tetap layak untuk mendapatkan apresiasi. Meski di dalamnya Eka juga mengumbar kata-kata jorok, setidaknya karya pertamanya yang cukup tebal dan membuat pembaca bisa lelah memelototi huruf-huruf yang kecil –dicetak dengan ukuran 10 karakter–, tampaknya masih memiliki kekuatan pada percikan pemikiran filosofis yang hendak dicecapkan pada pembaca, yakni absurditas sebuah kecantikan.
*N. Mursidi, cerpenis asal Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Sumber: JAWA POS – Minggu 1 Juni 2003.
*Rehal buku: Cantik Itu Luka: sebuah novel/ Eka Kurniawan/ AKYPress & Jendela, 2002.