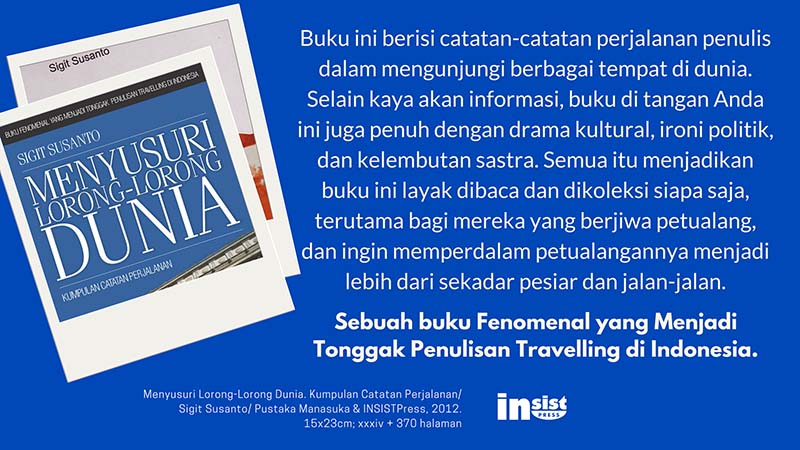Cakrawala Pengetahuan dalam Catatan Perjalanan*
Menulis catatan perjalanan keliling dunia bukan merupakan hal yang asing lagi bagi orang Indonesia. Tidak hanya berceceran di blog pribadi maupun milis komunitas, catatan perjalanan juga banyak yang sudah diterbitkan menjadi buku. Meskipun harus digarisbawahi, kebanyakan buku tersebut hanya memberikan perhatian pada pembahasan tentang how to. Deskripsi eksotisme sebuah lokasi wisata bertautan dengan gambaran variasi kuliner dan tawaran biaya murah. Dan dengan demikian buku-buku tersebut membatasi dirinya menjadi panduan perjalanan semata.
Hal tersebut bukan berarti tidak penting. Hanya saja catatan seperti itu memiliki banyak kekurangan. Yang paling mendasar adalah ia mengabaikan pengetahuan atau local wisdom yang bisa diserap dari lokasi-lokasi yang dikunjungi. Padahal, setiap tempat selalu merupakan akumulasi dari jalinan yang rumit antara aspek historis, sosial, dan politik. Karenanya, sebuah perjalanan akan semakin memberikan pelajaran jika kita memiliki pengetahuan tentang kelindan yang membentuk masa kini tempat tersebut.
Nah, inilah menariknya buku Menyusuri Lorong-Lorong Dunia karya Sigit Susanto ini. Buku yang dicetak ulang ini – pertama kali terbit tahun 2005 – adalah catatan perjalanan yang insightfull. Dalam buku ini kita tidak akan menemui panduan tentang biaya murah atau makanan. Namun lebih dari itu, kita akan membaca satu catatan perjalanan dengan cakrawala pengetahuan yang luas karena penuh referensi sejarah, sastra, politik, termasuk kebudayaan.
Sigit Susanto adalah warga Indonesia yang tinggal di Swiss. Bersama sang istri yang berkebangsaan Swiss, Claudia Beck, Sigit mengunjungi berbagai negara dan menuliskannya dalam sebuah tulisan yang memikat. Dalam buku ini, ada 16 esai yang mengabadikan perjalanan Sigit ke berbagai negara lintas benua seperti Belanda, Inggris, Kuba, Meksiko, dan Tunisia. Alih-alih sekadar opini yang subjektif, catatan-catatan dari kunjungan tersebut lebih tepat jika dikategorikan dalam jurnalisme sastrawi.
Jurnalisme ini mencoba memadukan antara prinsip jurnalistik dengan penulisan sastrawi yang indah. Gaya penulisan yang bertutur, memikat dan dilakukan melalui reportase ala jurnalis. Termasuk melakukan wawancara dengan “orang-orang biasa” di sebuah lokasi wisata. Tulisannya mengajak para pembaca untuk bertamasya ke sudut-sudut kebudayaan dengan kecermatan menata detail dan menempatkan plot. Referensi yang kaya menunjukkan bahwa bahan-bahan tulisan sudah dipersiapkan bahkan sebelum perjalanan dilakukan.
Berbagai literatur menuntun penentuan daerah-daerah yang akan dikunjungi. Artinya, pemilihan lokasi tidak hanya berdasarkan cerita “keindahan alam” semata. Sigit dan Istrinya biasa menelusuri rumah atau makam sastrawan besar yang ada di sebuah kota. Napak tilas tersebut ditampilkan dalam tulisan deskriptif tenunan antara lanskap arsitektur kota dengan biografi singkat sang tokoh. Seperti mengenalkan pembaca awam dengan pemikiran-pemikiran mereka.
Misalnya saja ketika mengunjungi museum Multatuli di Belanda. Sigit menuliskan biografi singkat penulis roman Max Havelaar yang memiliki nama asli Eduard Douews Dekker tersebut. Roman ini adalah karya pertama yang mengisahkan eksploitasi penjajahan Belanda di bumi nusantara. Multatuli hanya membutuhkan waktu satu bulan dengan menginap di sebuah losmen di Belgia untuk menulisnya. Sayangnya, tulis Sigit, roman ini baru diterjemahkan ke Bahasa Indonesia baru pada tahun 1972 oleh HB Jassin.
Ia membayangkan bahwa jika roman ini diterjemahkan ketika kolonialisme sedang berada pada puncaknya di tahun 1860, tentulah gelora revolusi rakyat bisa datang lebih cepat. Membaca tulisan ini memunculkan sebuah ironi.Max Havelaar yang memberikan serangan keras terhadap penjajahan Belanda justru menjadi buku bacaan wajib di sekolah-sekolah di negeri tersebut. Sementara di Indonesia, namanya seperti terlupakan.
Catatan menarik lainnya bisa kita lihat ketika Sigit pergi ke London dan mengunjungi makam Karl Marx. Banyak kisah menarik dari pemikir besar asal Jerman yang luput diketahui publik. Misalnya saja ketika Karl Marx kehilangan 2 anaknya yang meninggal. Ia terpaksa meminjam uang karena tidak memiliki cukup biaya untuk menguburkan anaknya. Masalah keuangan dan kelaparan yang begitu menyiksa Marx dan keluarganya tidak membuatnya putus asa menulis Das Kapital.
Setiap hari lebih dari 10 jam ia habiskan untuk menulis di British Museum. Puncak kesedihan Karl Marx adalah ketika anak dan cucunya yang menjadi penghiburnya sehari-hari harus pindah ke Prancis. Seperti dikutip Sigit, Marx begitu terpukul bahkan sampai mengatakan “I often run to the window when i hear children’s voices, forgetting the little fellows are across the channel.” Setelah itu Marx menghabiskan sisa hidupnya bersama Jenny istrinya sampai meninggal di tahun 1883.
Kisah-kisah semacam itu akan ditemui di sekujur buku ini. Penguasaan data yang padat juga menjadi modal untuk mencandra fakta kebudayaan yang ditemui dengan objektif. Satu hal yang penting agar tidak terjebak perasaan inferioritas sebagai warga dari negara berkembang. Secara tidak langsung, Sigit mengkritik orang-orang yang terlalu memberikan puja-puji ke negara-negara maju utamanya di Eropa, yakni orang yang bermental inlander yang masih bertahan di benak sebagian orang Indonesia yang keluar negeri.
*Wisnu Prasetya | Lansir dari: wisnuprasetya.wordpress.com – 10 Maret 2013.
*Rehal buku: Menyusuri Lorong-Lorong Dunia: Kumpulan Catatan Perjalanan/ Sigit Susanto/ Pustaka Manasuka dan INSISTPress, 2012.