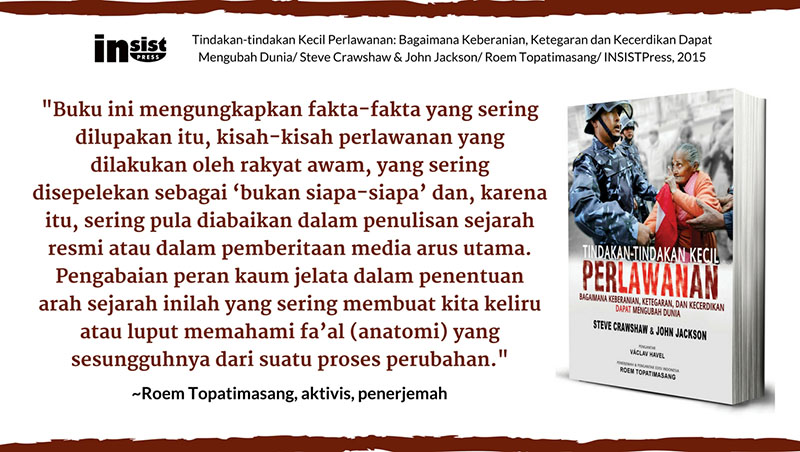Mogok Seks dan Para Atlet Yang Menjadi Pahlawan Perdamaian*
Bagaimana bila libido sexual diboikot? Apakah penyalurannya lewat upaya “swalayan” atau malah takluk dan setuju pada tuntutan pemboikot? Aristophanes menuliskan cerita Lysistrata yang mengorganisir pemboikotan sex kepada para lelaki (suami), yang bisa jadi memberi insiprasi WS Rendra ketika ia menulis puisi “Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta”. Aristophanes mungkin tidak pernah mebayangkan bila lakonnya secara harfiah dilakukan di beberapa negara berabad-abad kemudian.
Sekisar 20 tahun perang saudara di Sudan, antara Utara dan Selatan, para lelakinya baku bunuh tak berkesudahan. Sekisar 2 juta orang mati sia-sia dalam peperangan biadab itu. Lalu pada tahun 2002, kaum perempuan di Sudan Selatan yang muak dan lelah mengalami kekerasan dan kebiadaban perang, mulai mengambil inisiatif untuk menghentikan kekerasan dan kekejaman itu. “Samira Ahmed, seorang mantan guru besar di satu perguruan tinggi, bekerja dengan perempuan-perempuan dari dua kelompok etnis yang bertikai, mulai melancarkan aksi yang ia namakan “penelantaran seksual” (sexual abandoning). Tepat waktunya, ribuan orang segera bergabung.” Para perempuan tersebut beranggapan bahwa dengan melakukan mogok sex terhadap suami-suami mereka, maka para lelaki itu dapat ditekan untuk mengusahakan perdamaian. Karena semakin banyak perempuan yang bergabung dengan aksi tersebut, pada 2005 kesepakatan damai antara kedua belah pihak ditanda tangani.
Kenya, 2009, ketika orang takut mengungkap berbagai tindak kekerasan, pasca Pemilu, di antara para pemimpin politik, organisasi-organisasi perempuan mendesak dua lelaki pemimpin politik yang bertikai, PM Raile Odinga dan Presiden Mwai Kibaki, untuk mulai menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Untuk memperkuat desakan itu, kaum perempuan melancarkan aksi mogok sex (sex strike). Rukia Subow, salah satu pentolan organisasi perempuan itu berpendapat: “Kami melihat seks adalah jawabannya. Seks tidak mengenal suku, tidak punya partai politik, dan itu betul-betul terjadi di lapisan masyarakat paling bawah.” Aksi ini juga mendapat dukungan luas. Bahkan istri Perdana Menteri, Ida Olinga, memberikan dukungan dengan “jiwa dan raganya”. Aksi mogok seks itu diakhiri dengan doa bersama. Sang Perdana Menteri dan Presiden pun sepakat untuk berunding.
Kisah-kisah perjuangan yang di Kolombia juga terjadi dengan seruan “mari silangkan kaki melawan para lelaki yang doyan tindak kekerasan itu,” di samping kisah-kisah perlawanan “kecil” yang berdampak perubahan besar, pada bab “Perempuan Bilang Tidak,” diakhiri dengan cerita seorang perempuan di Mubende, Uganda, yang baru ditinggal mati suaminya. Seperti umumnya banyak negara, di mana perempuan dibatasi haknya untuk mempunyai lahan sendiri dan mewarisi harta gono-gini, Noerina Mubiru, janda itu, terlibat percekcokan dengan 10 orang keluarga almarhum suaminya yang datang ke rumahnya, di pagi ketika Noerina mau ke gereja. Keluarga suaminya menyodorkan daftar sejumlah harta yang akan diambil dari Noerina.
Noerina kemudian masuk ke kamar sebentar. Dan keluar lagi ke ruang tamu dengan tubuh bugil polos tanpa pakaian sehelaipun. Di depan para tamu itu ia lalu menunjuk ke selangkangannya dan berkata: “Kalian lihat, inilah salah satu barang yang paling dicintai suami saya.” Dan sambil menepuk bokongnya ia lalu berkata lagi: “Dan ini barang kedua yang paling ia sukai. Kalau kalian ingin mengambil barang-barang peninggalannya, silahkan mulai dengan dua barang ini, lalu saya akan memperlihatkan barang sisa lainnya kepada kalian!” Sang bapak mertua yang ikut di rombongan itu tersipu malu, dan tamu-tamu lainnya lari berhamburan keluar.
Sebuah gerakan sosial untuk perubahan yang massif, bisa dimulai oleh inisiatif kecil yang dimulai oleh 1-2 orang saja. Buku ini menyajikan sejumlah kisah nyata tentang hal-hal tersebut. Anda pasti kenal sang legenda ring tinju, yang belum tertandingi gaya dan sikapnya hingga kini. Ya, si “Mulut Besar” Muhammad Ali. Dengan kesadaran penuh akan risiko dari sikapnya, pada musim semi 1967, Ali tegas menolak wajib militer untuk menjadi tentara dan dikirim ke Vietnam yang sedang diperangi Amerika ketika itu. “Mengapa mereka meminta saya memakai seragam militer dan pergi puluhan ribu kilometer hanya untuk menjatuhkan bom dan membunuhi orang-orang berkulit coklat di Vietnam, padahal orang-orang yang mereka sebut Negro di Louisville diperlakukan seperti anjing dan disangkali hak-hak azasinya yang paling dasar? Tidak, saya tidak akan pergi puluhan ribu kilometer dari rumah untuk membantu pembunuhan dan pembakaran satu bangsa miskin, hanya untuk melanggengkan penguasaan para juragan kulit putih atas orang-orang berkulit gelap di dunia ini.”
Ali langsung dicomot. Gelar juara dunianya dicabut. Ia dipenjara (dari 5 tahuan jadi 3 tahun karena proses bandingnya berhasil), dan juga didenda US$ 10.000! Sejak saat itu ia menjadi legenda. Mendiang aktor kawakan Richard Harris mengomentari dengan kalimat sederhana: “Setiap petinju selama ini selalu berusaha dan bersedia menjual jiwa mereka demi mencapai gelar sebagai juara dunia tinju kelas berat. Apa yang dilakukan Ali? Dia justeru menemukan kembali jiwanya dengan melepaskan gelar juara dunia itu.”
Orang bisa dengan mudah dan piawai membicarakan ketidakadilan, dengan berbagai teori atau silat lidah lainnya. Tapi ujian sesungguhnya adalah dengan menghadapinya langsung.
Pantai Gading, negara di Afrika Barat, segera setelah kudeta 2002, negeri itu pecah dalam sebuah rangkaian konflik tak berkesudahan: Utara dan Selatan. Pembunuhan dan pemerkosaan menjadi cerita sehari-hari. Bahkan setelah perang usai, kecurigaan antar kubu tidak benar-benar usai.
Tapi ada seseorang yang membantu mengubahnya. Ia adalah Didier Drogba, pemain bola nasional, legenda dan eks pemain Chelsea. Ia bertekad untuk menyatukan kembali negerinya yang pecah itu. Sebagai kapten kesebelasan Tim Nasional Pantai Gading, The Elephants, ia selalu menekankan bahwa para pemain di Tim Nasional harus mewakili berbagai suku yang ada di negeri itu. Ia berhasil mewujudkannya! Ketika timnya berhasil lolos kualifikasi piala dunia 2006, seluruh rakyat Pantai Gading bersatu bergembira. Lalu pada tahun 2007, Drogba melangkah lebih maju, dengan langkah “sederhana” tapi revolusioner: dia mengumumkan bahwa pertandingan babak kualifikasi Piala Afrika akan diselenggarakan di Bouake, ibukota pemberontak di Utara yang tetap tak terjamah oleh pasukan pemerintah, kendati perdamaian telah disepakati pada Maret 2007. Drogba menggambarkan: Tanggal 3 Juni (hari itu) akan menjadi hari yang sangat dikenang. Hari itu akan menjadi hari kemenangan bagi persepakbolaan Pantai Gading, hari kemenangan seluruh rakyat Pantai Gading dan bisa dipastikan di sana akan ada perdamaian.” Sebanyak sekisar 25.000 rakyat Pantai Gading menyaksikan Tim Nasional mereka mengalahkan Madagaskar dengan skor telak, 5-0! Gol kelima diciptakan Didier Drogba.
Christophe Diecket, pejabat federasi sepakbola nasional, melukiskan: “Saya benar-benar terguncang. Istri saya menangis. Orang-orang di layar TV juga menangis. Kami rakyat Pantai Gading sudah memendam luka dalam dan penyakit ini sekian lama, tapi kami tidak menemukan cara untuk mengobatinya. Juga tidak bisa disembuhkan oleh siapapun juga selama ini. Hanya Drogba yang bisa!” Dan judul berita utama di koran nasional Pantai Gading ketika itu, menyebut: “Lima Gol Menghapus Lima Tahun Perang.”
Small Acts Of Resistance “Tindakan-tindakan Kecil Perlawanan” terbit pertama kali tahun 2010. Versi Indonesia telah diterbitkan INSISTPress di tahun ini, buku yang diterjemahkan dengan baik oleh Roem Topatimasang ini buku penting yang ringan dan enak dibaca.
*Pengulas: Saleh Abdullah | Lansir dari www.facebook.com/saleh.abdullah – 13 November 2015.
*Rehal buku: Tindakan-tindakan Kecil Perlawanan: Bagaimana Keberanian, Ketegaran dan Kecerdikan Dapat Mengubah Dunia/ Steve Crawshaw & John Jackson/ Roem Topatimasang/ INSISTPress, 2015.