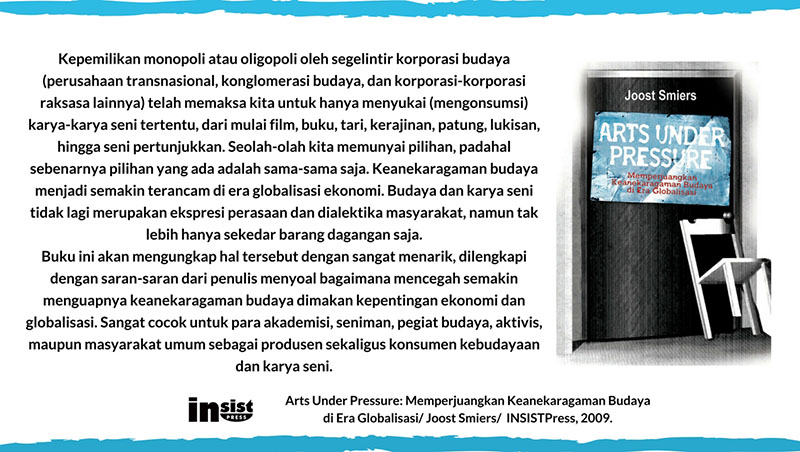Book Review: “Art Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi” (Joost Smiers, 2009)*
“Harus ada keseimbangan antara apa yang datang dari luar dengan apa yang berkembang biak di dalam lingkungan lokal tempat orang-orang jatuh cinta, berkonflik, membesarkan anak-anak, bekerja, menjadi pengangguran, mencuri, berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak-hak sosial mereka, mengadakan perayaan-perayaan mereka, minum minuman keras, menghisap ganja, membuat keputusan-keputusan hukum yang berkonsekuensi luas, dan meninggal dunia.” (hal. 318)
Sebagai seorang penikmat seni, menemukan buku ini adalah suatu anugerah. Apalagi ketika dikontekstualisasikan dengan politik. Sempat berpikir kalau buku ini belum ada di perpustakaan, tapi oh rupanya di sana ada juga (diketahui setelah membeli buku ini pffft). Selain itu, tentunya, bagian yang paling saya sukai adalah kalimat-kalimat sarkasme, satir, sindiran, atau apalah namanya—yang kadang sangat menusuk, true as fuck, dan wajib untuk ditertawakan.
Selama ini, pembahasan mengenai politik dan seni seringkali terpisah. Melalui buku ini, politik dan seni, keduanya saling mengkoyak-koyak satu sama lain: seni tak lagi ‘indah’ dengan keberagamannya karena telah dikomersilkan secara berlebihan. Dengan motif ekonomi, cara-cara politik digunakan untuk memaksimalkan keuntungan melalui ‘jual-beli’ karya seni. Singkatnya, buku ini membahas seni dari perspektif ekonomi politik—jika boleh disebut demikian, dan kaitannya dengan demokrasi.
Dari informasi di buku ini, penulis, Joost Smiers adalah Profesor Ilmu Politik Seni di Utrecht School of The Arts, Belanda, dan anggota Dewan Pengawas European Research Institute for Comparative Cultural Policy and The Arts (ERICArts). Wih, maaf kalau agak berlebihan dan memalukan, tapi “Ilmu Politik Seni” itu terdengar sangat asing bagi saya yang seorang mahasiswa Ilmu Politik. Ah, seandainya di sini ada kluster tersebut, rasanya ingin mendalaminya.
Hmm, mulai dari mana ya? Mungkin dari pemaknaan terhadap seni. Seni, bagiku adalah hal yang tidak bisa didefinisikan dengan mudah. Smiers menyebut seni sebagai arena pergulatan batin, konflik-konflik sosial, dan persoalan-persoalan status di dalam diri manusia, yang saling tarik menarik secara lebih padat dibandingkan dengan ranah komunikasi sehari-hari. Seni, oleh karenanya juga menjadi bagian dari perjuangan sosial (p. 3). Akan tetapi, “ada persaingan sengit di dalam banyak masyarakat mengenai siapa yang memperoleh kesenangan, kesenangan macam apa, kapan, dengan siapa, dan dengan harga atau pajak berapa besar” (Tiger 1992: 6). Seni, dengan demikian merupakan “medan tempur simbolik” (Shohat dan Stam 1994: 183).
Di lain kesempatan, saya pernah menonton diskusi virtual mengenai seni di Youtube. Seni kerap kali dimaknai sebagai sesuatu yang indah—bahkan harus selaluindah, indah dalam tradisi-tradisi tertentu. Saya lupa pembicaranya, tapi beliau mengatakan bahwa seni tidak selamanya dimaknai sebagai sesuatu yang indah karena seni merupakan pemaknaan atas kompleksitas pengalaman, di mana hal itu membedakan seni dengan agama, sains maupun filsafat—tetapi dapat pula mencakup agama, sains maupun filsafat. Beliau kemudian menggunakan konsep Husserl tentang “Lebenswelt” yang erat dengan fenomenologi. Menurutnya, dunia manusia itu konkrit, pra-reflektif, kompleks dan ambigu. Dunia manusia tidak hanya dialami begitu saja, tetapi juga dihayati. Dan seni, merupakan arena untuk menginterpretasikan the fucking “Lebenswelt” itu secara tidak klise sebagaimana komunikasi sehari-hari misalnya. Singkatnya, seni merumuskan hal-hal dalam realitas yang sering tak terumuskan.
Nah, menanggapi seni sebagai “medan tempur simbolik” rupanya sangat berkaitan dengan politik. Siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang sampai kepada audiens, dalam kualitas apa, dengan muatan apa, dan dilingkupi atmosfer macam apa? Adalah korporasi budaya, menurut Smiers. Hal yang tampaknya sepele tapi fatal, misalnya adanya daftar peringkat lagu “100 teratas” yang sering kita temui di media-media. Daftar-daftar itu begitu hebat tapi abstrak, dan bila mau bongkar-bongkaran—seolah ada kisah-kisah tertentu yang paling bermakna dibandingkan makna lainnya, ada “medan tempur simbolik” yang menjadikan lagu-lagu tertentu lebih disukai mayoritas audiens, ada “medan tempur simbolik” yang menjadikan lagu-lagu tertentu lebih laris dibandingkan yang lain, dan yang namanya “laris” pasti berkaitan dengan motif ekonomi. Hahahaha.
Akibat adanya “kesenangan mayoritas pasar”, para seniman (yang hidupnya dari seni ataupun tidak sepenuhnya) pada akhirnya dipaksa menciptakan karya seni “aman” yang sesuai arus. Demi kepentingan korporasi budaya dan “selera” pasar (jika masih bisa disebut selera), seni telah dicederai! Seni yang dikomoditaskan (secara berlebihan) tidak lagi menjadi ajang ekspresi diri, tapi hanya memenuhi keinginan pasar, menuruti tata nilai/ sistem yang sudah ada.
“Seni adalah produsen penting ideologi kita,” kata Smiers. Ideologi menurut Stuart Hall adalah “kerangka mental—mencakup bahasa, konsep, kategori, perbandingan pemikiran, dan sistem representasi—yang diterapkan oleh kelas-kelas dan kelompok-kelompok sosial yang berbeda untuk memahami, mendefinisikan, mengerti, dan juga mengubah cara-cara masyarakat berfungsi” (p. 18). Melalui industri film sebagai bisnis raksasa misalnya:
“Di balik aspek industrial, ada juga aspek ideologis… Pertempuran sejati yang berlangsung saat ini adalah memperebutkan siapa yang akan diperkenankan mengontrol citra dunia, yang dengan itu akan dapat menjual gaya hidup tertentu, budaya tertentu, produk-produk tertentu, dan gagasan-gagasan tertentu.” (p. 18)
Pelik. Munculnya kritikus-kritikus tetek bengek semakin mengarahkan massa untuk menilai apa yang bernilai dan apa yang merupakan omong kosong saja dalam aktivitas artistik ini. Atau budaya kekerasan yang semakin mewabah di berbagai media. Hmm lagi-lagi aku menemukan buku yang membeberkan relasi antara fiksi dan fakta.
“Denise Caruso mencatat bahwa media ultra-kekerasan secara sistematis menerapkan teknik-teknik psikologis yang sama untuk melakukan desensitization, conditioning, dan vicarious learning, seperti yang digunakan selama perang Vietnam untuk mengajari para prajurit agar bisa membunuh secara otomatis di pertempuran yang mereka hadapi, sambil tetap menghormati kekuasaan dan dapat membuat pembedaan-pembedaan instan antara mana kawan dan mana lawan.” (p. 237)
[Desensitization, metode untuk menurunkan tingkat kepekaan. Dapat diterapkan pada bidang kedokteran untuk penanganan alergi (misalnya dengan cara injeksi bertahap) ataupun di bidang psikologi untuk mengatasi phobia dengan menghadapkan klien pada hal yang menjadi objek atau situasi phobia secara berulang kali, baik dalam keadaan alamiah ataupun buatan.
Conditioning atau pengkondisian merupakan metode untuk mengendalikan atau memengaruhi tingkah laku ataupun cara pikir (orang ataupun binatang) dengan menggunakan proses pelatihan bertahap disertai “hukuman” dan “penghargaan” sesuai tingkah laku yang ditampilkan.
Vicarious Learning, metode konstruksi tingkah laku dengan melihat atau membayangkannya sebagai hal yang dialami sendiri, biasanya diterapkan pada terapi kelompok.]
Mengenai budaya kekerasan, Baudrillard dan beberapa pemikir lain mengajukan istilah “tubuh-tekno” yang dapat dilukai sesering yang kita inginkan. Tubuh-tekno merupakan hasil objektivasi diri yang dikonstruksi melampaui kepercayaan dan melampaui kenyataan (atau virtual).
Selanjutnya dari aspek industri. Smiers-mengaku sebagai pascamodernis-lebih jauh lagi mengkritik tentang Hak Kekayaan Intelektual atau hak cipta. Berdasar pada konsep romantik, “pencipta adalah seseorang yang menciptakan sesuatu yang asli sepenuhnya, menciptakannya begitu saja dari ketiadaan” (p. 107). Hak cipta saat ini lebih merupakan alat bagi konglomerasi budaya (dan sedikit seniman tertentu) untuk terus menghasilkan uang—tidak hanya dari penayangannya oleh si ‘pencipta’ tetapi oleh siapapun yang menggunakan karya tersebut akan dikenai sekian biaya. Smiers kemudian berpikir ke arah penghapusan hak cipta yang akan menguntungkan seniman terutama yang berasal dari negara-negara Dunia Ketiga (p. 84)—alasannya adalah demokrasi. Gokil! Selama ini kita cenderung berpikir untuk mengklaim apa-apa yang kita buat, meniru para seniman terkenal, dengan dalih menghindari plagiarisme dan sebagainya. Perlu dibedakan lagi sih, mana yang disebut “plagiarisme” dan yang disebut “terinspirasi oleh”.
“Rezim yang berpusat pada pencipta benar-benar dapat memperlambat kemajuan ilmiah, menghancurkan peluang-peluang kreativitas, dan mengurangi ketersediaan produk-produk baru.” (p. 327)
Mungkin ini sangat radikal, tapi Smiers telah menyediakan katalog solusi untuk mengatasi ketimpangan yang selama ini diakibatkan oleh ilusi hak cipta maupun bentuk-bentuk penindasan korporasi budaya. Apa katalog solusi yang diberikan Smiers? Smiers membaginya menjadi dua, yakni perihal Regulasi Kepemilikan dan Regulasi Isi sebagai upaya untuk menjauh dari konglomerasi budaya. Regulasi Kepemilikan memiliki tujuan untuk memelihara sebuah keseimbangan keanekaragaman kepemilikan perusahaan budaya, untuk membatasi paradigma yang digerakkan oleh pasar, untuk melindungi komunitas-komunitas yang tidak secara normal mendapat tempat di pasar, serta untuk memastikan adanya akuntabilitas para pemilik terhadap publik (p. 275). Regulasi Isi mengatur mengenai konten apa saja yang akan disebarluaskan dan memastikan tidak ada ketimpangan di dalam pelaksanaannya. Katalog solusi Smiers inipun telah banyak ia sampaikan di konferensi-konferensi, seperti konferensi bertajuk Regulations in Favour of Cultural Diversity tahun 2003 di Amsterdam. Lebih jelasnya mengenai katalog solusi yang ditawarkan Smiers, silakan baca sendiri.
Apa yang dilakukan Smiers mungkin belum menunjukkan pengaruh yang nyata dan dekat dengan kita. Saya pun sedikit pesimis. Ketika kita sudah terbiasa mengkonsumsi produk-produk budaya yang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan besar konglomerasi budaya hingga telah menjadi ‘ideologi tanpa nama’bagi masyarakat, lantas bagaimana serentetan katalog solusi ini dapat dijalankan? Singkatnya, bagaimana jika terjadi benturan antara katalog solusi tersebut dengan ‘ideologi tanpa nama’ hasil bentukan konglomerasi budaya? Hahahahahahaha.
Benar kata dosen saya bahwa politik rekognisi memang tidak bisa dipisahkan dari politik redistribusi. Kita sedang memikirkan bagaimana caranya para seniman kecil yang tidak memiliki akses terhadap korporasi budaya tetap bisa diakui, bahkan mendapatkan kesetaraan tanpa harus menghomogenisasi konten/ isi karya seni di pasaran, sembari menciptakan distribusi keuntungan/ kesejahteraan yang lebih adil. Masih banyak sekali yang ingin disampaikan tentang buku ini, salah satunya ketika Smiers membicarakan bahwa keragaman budaya tak ada bedanya dengan keragaman alam—budaya dapat ditambang hingga habis terpakai. Silakan baca sendiri.
Di bagian penutup buku ini, Smiers mengutip kata-kata penyair Belanda Lucebert: “Semua yang berharga tidak mampu bertahan.” Ia membenarkan hal itu, namun bukan berarti harus jadi pesimis.
Jika setelah selesai penulisan buku ini Smiers memutuskan untuk memainkan ‘seruling’ lagi sebab hal itulah yang sudah lama tidak sempat ia lakukan, maka saya akan… Menabuh gong? Menulis puisi? Bermain gitar? Ah, ‘mendengarkan’ alunan musik dulu saja.
Para seniman memunyai kesempatan unik mengonfirmasi, “bahwa kehidupan itu tetap indah untuk dijalani, terlepas dari segala apa yang sudah terjadi.” – Ger Groot, “Kunst in tijden van Dutroux”, De Groene Amsterdammer, 22 Oktober 1997.
Sekian.
*Oleh: Avrita Lianna. Sumber: runtahlife.wordpress.com – 19 Oktober 2017.
•Rehal buku: Arts Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi/ Joost Smiers/ Umi Haryati (penerjemah), Fitri Indra Harjanti (penyunting)/ INSISTPress, Febuari 2009.