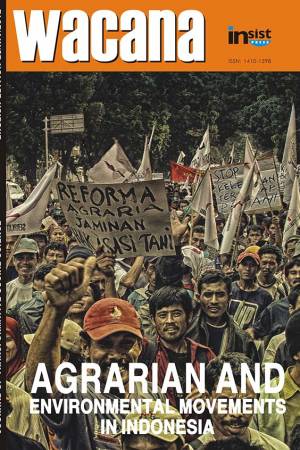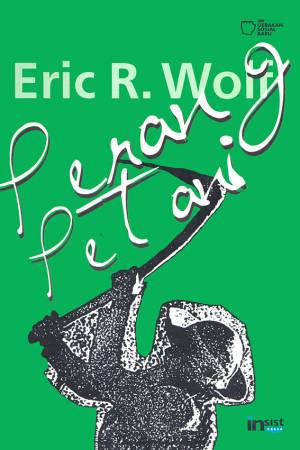| Catatan Penutup |
CATATAN PENUTUP
Orang Papua Mesti Ambil Alih Kendali
Dr. Benny Giay
Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Walter Post, Sentani, Jayapura, Papua
Email: bgiay2012@gmail.com
Saya menyambut baik publikasi tulisan-tulisan tentang tanah Papua dalam Jurnal Wacana edisi ini. Publikasi ini merupakan upaya dari para intelektual dan pegiat isu-isu sosial di Indonesia untuk secara kritis melihat persoalan tanah di Tanah Papua. Persoalan tanah di Papua tidak dapat dilepaskan dari masalah sejarah dan rasisme. Sama seperti bangsa-bangsa penjajah dari Eropa, Indonesia datang ke Papua dengan anggapan bahwa Papua adalah tanah kosong. Orang Papua dianggap tidak memiliki sejarah, tidak memiliki kebudayaan dan primitif. Sambil secara sepihak mengangkat diri mereka sebagai guru peradaban, orang-orang yang datang dari luar ini menguasai tanah dan manusia Papua.
Sebagian pemimpin Indonesia menganggap Papua sebagai bagian penting untuk membangun Indonesia modern. Dalam mengklaim Papua sebagai bagian dari Indonesia dalam debat BPUPKI pada 1945, Sukarno dan Mohammad Yamin menggunakan Sriwijaya dan Majapahit untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa. Berbeda dengan Mohammad Hatta dan kaum demokrat lain yang menganggap bangsa Papua yang berkebudayaan Melanesia berhak membangun negara-bangsa mereka sendiri, Sukano menghidupkan mitos Wannim dalam kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Prapanca untuk mengonfirmasi diri, memperkuat diri, menampilkan Indonesia yang modern di depan publik Indonesia dan dunia. Alasan mitos sejarah Indonesia Raya ini juga dipakai juga untuk mengklaim Malaysia pada 1964 (“Ganyang Malaysia”) dan setelah itu Timor Leste pada 1975 (aneksasi Timor Leste). Barangkali karena sebagai negara-bangsa, Indonesia sendiri kurang percaya diri dan masih goyahkah? Jadi Papua adalah salah satu bahasa, rujukan politik propaganda untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai sebuah negara modern, Indonesia yang modern. Tidak ada Indonesia modern tanpa Majapahit, dan tidak ada Indonesia modern tanpa Papua. Yang saya mengerti Sukarno dan Mohamad Yamin memegang itu.
Antara 1945, ketika Indonesia membebaskan diri dari cengkraman kolonial Belanda, sampai era 1960-an, orang Papua juga bangkit berusaha untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun usaha itu terhalang oleh kemauan Indonesia untuk tetap menjadikan Papua sebagai bagian dari Indonesia Raya itu. Usaha untuk menguasai Papua dilegitimasi dengan arogansi supremasi rasial. Pada 1960-an, Indonesia menyebarkan propaganda politik di Irian Barat (nama Papua saat itu) dengan klaim bahwa Indonesia datang untuk menyejajarkan rakyat Irian Barat dengan suku-suku di Indonesia yang sudah maju, beradab, dan lebih dulu merdeka. Mereka menganggap tanah Papua kosong dan orang Papua tidak beradab, primitif, dan tertinggal. Anggapan ini dipakai untuk memperkuat dirinya di depan rakyat Papua, di dunia, dan barangkali di depan orang Indonesia sendiri saat itu. Dengan begitu, secara sepihak Indonesia mengangkat dirinya sebagai guru. Tanpa meminta penunjukan atau ‘SK’ dari orang Papua, langsung dia mengangkat diri sebagai guru peradabanan, guru kemajuan, guru pembangunan, guru baku tipu, guru korupsi, dan lain sebagainya. Orang Indonesia ingin membangun orang Papua, ingin mengganti koteka dengan celana, sali dengan kebaya, dan lain-lain.
Sikap Indonesia itu didukung oleh sekutunya, Amerika Serikat, yang pada masa itu juga mulai mengincar kekayaan alam Papua. Yang saya baca, misalnya dari karya Danilyn Rutherford (2019), Sukarno mengambil istilah primitif untuk menggambarkan kebudayaan orang Papua dari Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Istilah itu menjadi pegangan Indonesia untuk mengambil Papua dan menganggap Papua sebagai tanah kosong, dan juga untuk memperkuat dirinya. Saat itu, Indonesia ingin berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
Jadi proses penguasaan tanah didasarkan pada misi mengangkat orang Papua dari ketertinggalan, didasarkan pada ‘SK tak tertulis’ bahwa orang Indonesia adalah guru peradaban dan guru pembangunan orang Papua.
Penyangkalan kebudayaan dan peradaban orang Papua disertai dengan penghapusan sejarah dan pemberangusan tradisi intelektualnya. Sehari setelah Indonesia masuk Papua, pada 2–3 Mei 1960, tentara Indonesia membakar berbagai buku dan dokumen tentang sejarah politik, kebudayaan, dan sosial orang Papua. Mereka datang ke rumah-rumah dan kantor-kantor. Semua dokumen termasuk pamflet dibakar di depan kantor New Guinea Raad (kini kantor Dewan Kesenian Papua di Jayapura). Kita bisa membaca kisah soal pembakaran dan penjarahan yang dilakukan tantara Indonesia di memoir Jenderal Acub Zainal (I love the Army).
Mulai hari itu, di mata Indonesia orang Papua adalah bangsa tanpa kebudayaan, bangsa tanpa sejarah, bangsa tanpa masa lalu dan tanpa masa depan. Indonesia yang akan berikan semua ke rakyat Papua—budaya, sejarah, pendidikan, masa lalu, dan impian masa depan, semua. Intinya, orang Papua dianggap tidak ada, kecuali kalau mereka menuruti kemauan pemerintah Indonesia. Sejak itu, orang Papua, termasuk gereja-gereja, terbagi dua: mereka yang mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mereka yang melawan. Tidak ada wacana di luar nasionalisme dan proyek NKRI karena di luar itu berarti melawan negara.
Orang-orang yang mempertahankan tanah dari penguasaan, serta mereka yang menghidupkan kebudayaan dan meluruskan sejarah, dianggap sebagai musuh negara. Sambil tanah dan kekayaan alamnya dikuasai, orang Papua diperlakukan secara rasis dan terus menerus menjadi sasaran operasi militer. Bukan hanya di kampung-kampung, mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di kota-kota di Indonesia pun seringkali menjadi sasaran rasisme orang masyarakat dan aparat Indonesia. Peristiwa rasisme terhadap orang Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu merupakan sebuah tamparan untuk kita semua. Insiden itu menggemparkan dan tidak direncanakan, tapi mencerminkan satu hal: Indonesia yang munafik.
Penguasaan tanah dan rasisme ini telah berlangsung lama. Pada awal abad XX, pendeta A.T. Baud, seorang pendeta Protestan Belanda (kini menjadi GKI) yang ditugaskan ke Fakfak, mencatat bahwa orang-orang di Fakfak (atau Wwanim) mengungsi ke hutan-hutan karena menghindar dari pedagang budak dan ekspedisi hongi yang dijalankan oleh orang-orang Makassar, Tidore, Ternate, Seram, dan Belanda. Banyak orang Fakfak dijual dan dijadikan budak sejak abad XVII. Orang dari Seram, Goram, Tidore, dan Ternate ini disebut sebagai ‘negara nusa’ dan dianggap sebagai orang asing (amber). Kerajaan-kerajaan ini sudah biasa mengambil orang Papua sebagai budak. Ketika orang-orang Papua lari ke hutan, mereka mengambil tanah-tanah yang ditinggalkan. Orang Papua tidak bisa melepaskan kisah sejarah panjang perampasan tanah seperti ini.
Penguasaan tanah, penghancuran kebudayaan, pembakaran buku-buku, dokumen, serta tradisi intelektual adalah penghancuran sejarah, jiwa, dan semangat orang Papua. Menghadapi sejarah kelam seperti itu, tidak ada jalan lain bagi orang Papua, selain mengambil alih kendali kehidupan, membangun Papua Baru.
Daftar Pustaka
Giay, B. 2000. Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua. Waena, Jayapura: Deiyai.
Hendrowinoto, N.K.S. 1998. Acub Zainal, I love the army. Jakarta: Yayasan Biografi Indonesia.
Rutherford, D. 2019. Living in the Stone Age: Reflections on the Origins of a Colonial Fantasy. Chicago: Chicago University Press.
Saafroedin, B. dan N. Hudawati. 1998. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945–22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
|